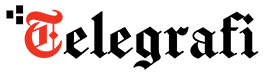Telegrafi – Berbicara tentang Adam Smith tak dapat dipisahkan dari konsep kapitalisme yang bertumpu pada dogma konsep “nilai uang berdasarkan waktu’” Tapi, benarkah gagasan ekonomi-politik Smith memiliki hubungan paralel dengan konsep yang saat ini mewarnai jagad ekonomi global tersebut?.
Tulisan ini menawarkan sebuah hipotesa berbeda tentang hal itu dan sebuah tinjauan tentang efeknya terhadap realitas ekonomi global dewasa ini.
“Bukan dari kebaikan tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita dapat menyantap makan malam kita. Tapi kepedulian mereka pada kepentingan mereka sendiri.” (Adam Smith)
Era Depresi dan Kapitalisme
Perang selama sembilan tahun dengan Perancis pada abad XVII memberikan hantaman serius terhadap perekonomian dan perpolitikan Inggris. Kondisi itu diperburuk dengan terjadinya pemberontakan pada tahun 1745, yang kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin di negeri itu.
Sebagai solusi, kebijakan radikal yang ditempuh saat itu adalah memprivatisasi Bank of England pada tahun 1694, untuk keperluan pembangunan armada perang Inggris yang menelan biaya sebesar £ 1,2 juta.
Dana tersebut dikenakan bunga sebesar 8 % pertahun, ditambah biaya administrasi sebesar £ 4.000. Nominal yang fantastis besarnya itu kemudian dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk pajak.
Pada era Smith, koin inggris hanya memiliki kadar 1/3 dari nilai wajar. Begitu pun dengan uang kertas sebagai bank notes, tak lagi dikeluarkan berdasarkan jaminan yang riil.
Sementara kapitalisme sendiri, menempatkan modal dalam hal ini uang sebagai komoditas, bahkan subjek dari perekonomian. Efeknya, pajak implisit tersebut memicu volatilitas nilai mata uang yang berimplikasi terhadap inflasi. Inilah realitas yang mewarnai proses lahirnya gagasan Smith.
Smith memijakan teori ekonominya pada basis moral, tak berdiri sendiri secara parsial dalam kerangka nalar kapital. Ini yang sering dialpakan oleh para pembaca Smith.
“Pengatur sistem alam raya, pemelihara kebahagiaan universal dengan seluruh rasionalitas dan perasaan setiap entitas adalah peranan Tuhan dan bukan urusan manusia,†demikian Smith menuliskannya di The Theory of Moral Sentiments yang terbit tahun 1759.
Karena itu, The Wealth of Nations yang terbit 17 tahun kemudian, harus dipandang dalam dua perspektif: ide otentik Smith dan aksioma yang dipaparkannya. Selama ini, kita cenderung terjebak pada satu persepktif saja dalam membaca gagasan Smith.
Smith menaruh perhatian khusus terhadap buruh sebagai variabel utama dalam produktifitas yang merupakan nilai rill ekonomi. Dalam perspektif Smith, tak ada perbedaan antara komoditas produksi dengan produktifitas tenaga kerja.
Negara dalam hal ini harus melakukan liberalisasi terhadap industri manufaktur. Sebab hal tersebut berpengaruh positif terhadap ketenagakerjaan, sebagai solusi terhadap problem riil yang dihadapi masa itu.
Berdirinya negara persemakmuran dan perdagangan internasional lainnya mengacu pada efisiensi dan efektifitas dalam menghasilkan produk. Keringat para buruh menjadi sentralnya. Inilah yang membuat Marx menuding Smith melakukan eksploitasi terhadap para buruh.
Kritik Marx, sebenarnya tidak tepat dan tidak relevan, jika kita dudukkan gagasan Smith secara otentik. Gagasan otentik Smith menempatkan buruh pada posisi yang terhormat sebagai subjek, bukan sebagai objek eksploitasi, rotasi proses ekonomi.
Revolusi Industri
Kemudian Smith meninggal pada tahun 1790, sebelum era Revolusi Industri yang baru rampung pada tahun 1850. Revolusi Industri merupakan era baru dimana produktifitas para buruh tidak lagi sejajar dengan produksi.
Pembuatan pin-pin yang membutuhkan setidaknya lima tahapan proses, yang sebelumnya dikerjakan oleh para buruh, kini dilakukan dengan mesin yang lebih memiliki nilai ekonomis. Sehingga Friedrich Hegel, sang filsuf kenamaan itu, melihat mesin-mesin yang tercipta bukan hanya mencetak produk masal, namun juga kemiskinan masyarakat.
Padahal, teori Smith sendiri tentang tenaga kerja sebenarnya tidak dalam kerangka yang diterapkan pada era industri itu. Smith tak pernah menegasikan eksistensi buruh sebagai bagian penting dalam proses produksi.
Melihat semua ini, pertanyaan puncaknya: apakah realitas ekonomi global yang berkembang saat ini lahir dari embrio, dan relevan dengan, gagasan otentik Adam Smith?
Secara tekstual gagasan Smith memang membuka akses bagi terjadinya liberalisasi pasar. Namun, secara kontekstual itu dilakukan sebagai strategi mengatasi kondisi ekonomi saat itu, tapi dengan tetap tidak memisahkannya dari pertimbangan moril, yaitu memanusiakan manusia sebagai subjek dalam proses ekonomi, tidak menempatkannya sebagai objek.
Produktifitas vs Kesejahteraan
Lalu, apa relevansinya dengan ekonomi global saat ini? Hal itu terletak pada indikator yang digunakan dalam mengukur sebuah proses ekonomi. Contoh sederhana yang terjadi di Jakarta. Untuk menggenjot perolehan pendapatan daerah, pemerintah mengeluarkan IMB dan BPKB secara progresif. Secara PAD, Jakarta tumbuh pesat dan angka ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Tapi, konsekuensi dari ‘pertumbuhan’ model ini adalah kemacetan dan banjir yang makin tidak terkontrol.
Dalam skala nasional, seperti baru-baru ini diberitakan Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan menembus 6,8%. Pertanyaan fundamentalnya: apa yang dikorbankan untuk mencapai angka tersebut? Keadilan sosial! Keadilan ekonomi mensubordinasi keadilan sosial. Produktifitas materiil menomorduakan kesejahteraan sosial.
The Wealth of Nations banyak bercerita tentang ketidakadilan sosial. Smith menaruh perhatian besar pada masalah tersebut. Bahkan, tak ada terminologi “kapitalisme” dalam buku Smith itu. Istilah tersebut menjadi tema sentral justru 60 tahun setelah meninggalnya Smith, dalam buku yang ditulis oleh Karl Marx.
Oleh : Ali Heyder. | Photo Credit : AP Photo