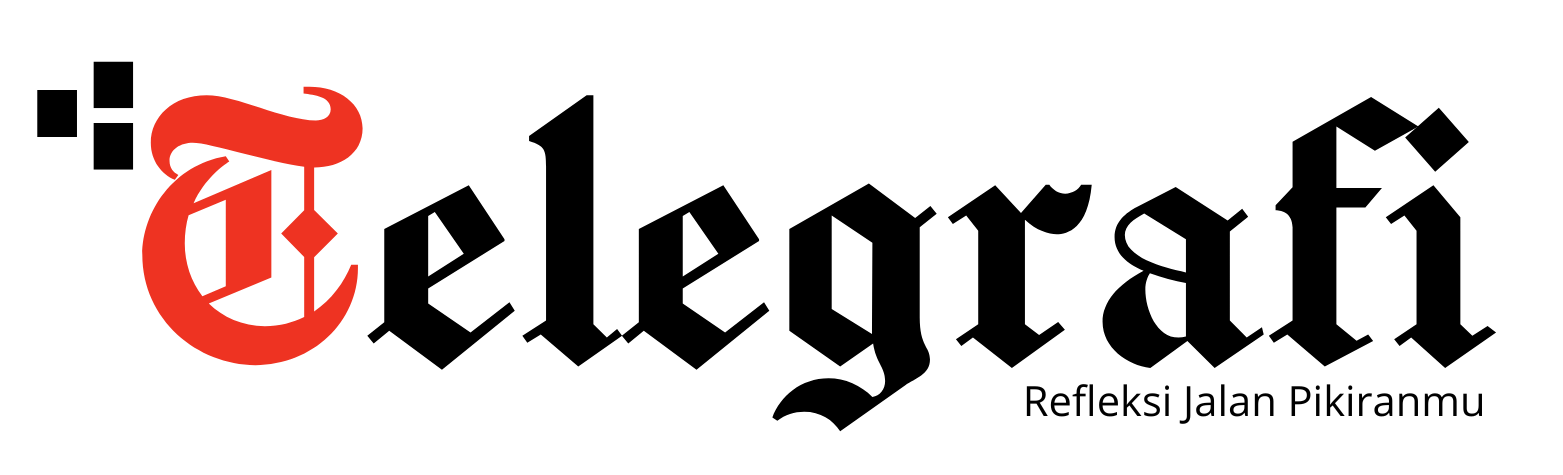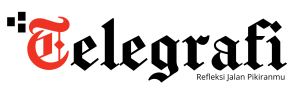Namaku Puisi. Entah mengapa aku diberi nama Puisi. Aku tak tahu banyak soal pemberian nama itu. Ayahku hanya bilang bahwa dia memberiku nama Puisi, lantaran kegilaannya. Kegilaan sama apa aku tidak tahu. Kegilaan sama puisi? Mungkin. Tapi, entahlah. Walaupun namaku Puisi, tapi ayah selalu memanggilku Anak Senja.
Hampir satu minggu ayah kebingungan. Tindak-tanduknya seperti orang linglung. Di saat senja, ia selalu duduk di kursi taman kota di bilangan selatan Jakarta. Rambutnya gondrong riap-riapan dan hanya dengan jari ia merapikan rambutnya. Ya, itulah ayahku. Ayah kandungku? Tentu tidak!
Ayah menemukanku masih dalam bedongan yang rapi terbungkus kain lembut, tebal, dan hangat motif bunga-bunga. Mungkin ibu kandungku yang menaruhnya. Mungkin ayah kandungku yang membuangnya. Mungkin penculik yang tak mau ambil resiko. Mungkin juga…ah, entahlah. Siapa yang membuangku saat itu. Aku hanya menangis dan tak ada siapa-siapa. Suasana sepi dan remang.
Saat itu, ayahku baru saja pulang dari kantornya, sebuah media surat kabar. Dengan tas kamera yang nemplok di punggungnya, ia melaju dengan sepeda motornya. Entah kenapa hari itu ia parkirkan sepeda motornya di pusat perbelanjaan yang tak jauh dari taman kota. Ia pun memilih berjalan. Ya, jalan ke taman kota, tempat biasa ia melepas lelah dan menggenapkan kegelisahannya. Ia berjalan santai seirama dengan puluhan pejalan kaki dan lalu-lalang kendaraan.
Dalam kekosongannya, Ayah memilih jalan pintas, berbelok ke arah tempat pembuangan sampah. Lengang. Jalan itu terlihat kosong. Tak lama, bau sampah mulai menyengat. Angin yang menyebarkan aroma kurang sedap itu. Di sepi dan sendiri.
Di senja itulah sejarahku punya ayah dan karena ‘di senja itulah’ aku dipanggil Anak Senja.
Ayah mendengar tangisanku. Mungkin saat itu juga Tuhan mengirimkan utusannya, penyelamatku. Tuhan pulalah yang memilihnya menjadi malaikatku. Malaikat lucu, gondrong, nyentrik, tapi baik hati. Ah, ayah, aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku selalu merindukanmu.
Ayah berhenti sebentar dan melihat ke arahku. Ia terkejut melihat seorang bayi tergolek di samping bak sampah. Entah apa yang ada dalam hati dan perasaannya saat itu. Mungkin dia panik, bingung, gembira, sedih atau entahlah. Ia memungutku. Ia mencermati wajahku. “Ini anak siapa?” ucapnya pelan, nyaris berbisik. Ia melihat sekeliling. Tapi tetap sepi, temaram, dan bau.
“Ya, mungkin inilah cara Tuhan mengirim puisi untukku. Puisi yang membuatku seperti orang lingling hampir seminggu ini. Tuhan Maha Indah, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, dan Tuhan Maha Pemberi. Ia kirim puisi yang sebenar-benarnya puisi untukku. Ya, kamulah anakku, kamu puisi itu,” ucap ayahku mengisahkan masa laluku.
Itulah mula kisahku. Tentang nama Puisi dan panggilan Anak Senja buatku. Ayahku yang memberikan nama dan panggilan itu. Ayah kandungku? Tentu tidak.
Ayahku adalah lelaki hebat. Selain ayah, ia menjadi ibu buatku. Aku mengenal ayah dan ibu dari sosoknya. Lelaki berambut gondrong riap-riapan dan hanya menyisir dengan jari-jari tangannya. Ia merawatku, memandikanku, menyuapiku, dan mengajakku bermain. Tak lupa, ini yang tak dimiliki oleh ayah-ayah yang lain. Ayah meninabobokanku dengan puisi-puisinya.
Aku mendengar cerita Pranacitra-Rara Mendut dari puisinya. Aku mendengar Majapahit dari puisinya. Aku tahu Prancis, Belanda, Jepang, dan Cina dari puisinya. Aku selalu dibacakan puisi tentang Carl Marx, Soekarno, Tan Malaka, Jalaludin Rumi, Rabiah al Adawiyah, Ibnu Sina, Foucault, Derida, Sigmund Freud, Ferdinand de Saussure, Mahatma Gandhi, Einstein, dan banyak lagi dari puisi-puisinya.
Ada satu puisi yang selalu aku ingat; Soekarno. Ayah memetik kalimat Soekarno dalam puisinya, yang salah satunya… “beri aku aku 10 pemuda, akan aku ubah dunia…” Hebat! Keren!
Itulah Ayahku. Lelaki hebat yang aku kenal. Ayah kandungku. Tentu tidak. Bahkan dia lebih dari sekedar ayah kandung. Dia tidak lagi sekedar ayah, tapi sahabat, kakak, dan kekasihku. Ya, kekasihku!
Pagi mengajakku bangun kali ini. Cahaya yang menerobos kisi-kisi jendela seperti tepukan tangan suci bunda di tubuhku. Ah, aneh rasanya aku menyebut nama bunda. Sungguh, meskipun aku ingin seperti sahabat-sahabatku memiliki banyak sebutan untuk seseorang yang melahirkannya. Ibu, mama, mami, bunda, mbok, emak, nyak, umi, dan banyak lagi sebutan itu. Tapi aku? Ah, ibu bagiku adalah seorang lelaki berambut gondrong yang memberiku nama puisi dan memanggilku Anak Senja.
Banyak sahabatku yang menanyakan kenapa namaku hanya Puisi. Kok tidak ada tambahan lainnya, semisal Diah Puisi, Mentari Puisi, atau Laskar Puisi. Tidak! Ya hanya puisi. Itu saja.
Pernah suatu ketika aku tanyakan ke ayahku, kenapa namaku hanya puisi. Kok tidak ada nama lain di depan ada di belakangnya. Ayahku hanya diam dan melihatku. Di tersenyum.
“Tak ada yang mampu mendampingi keindahan nama puisi,” ucapnya. “Suatu saat kamu akan mengerti, kenapa namamu puisi. Dan, tidak ada nama lain yang mendampingi di depan atau di belakangnya.”
Puisi adalah jiwa. Puisi adalah kebebasan. Puisi adalah keindahan. Puisi adalah pemberontakan. Puisi adalah aku, kamu, dia, mereka, dan siapa saja. Puisi adalah kehidupan. Begitulah aku dan nama puisi buatmu.
“Trus kenapa Ayah memanggilku Anak Senja?” tanyaku.
Ayah kembali hanya tersenyum.
“Karena senja itulah ibu kandungmu. Senja itulah yang melahirkanmu. Senja itulah yang mempertemukan kita. Senja itu pulalah yang menjadikanku seorang ayah. Ya, ayahmu ini.”
Senja rubuh di ufuk barat. Di sebuah apartemen di tepian Jakarta, aku duduk menikmatinya. Bersama ayah? Tentu. Ah, tidak. Kali ini ia menjadi kekasihku. Ya, kekasihku.
Di senja itu, ayah mengajariku untuk memiliki banyak cinta dan aku harus menyemestakan rasa. Pada sahabat, pada gunung, pada laut, pada udara, pada tanah, dan juga pada Tuhan. Aku harus memiliki banyak cinta untuk semua, aku harus memiliki banyak cinta untuk sesama. Tak terkecuali untuk ayahku, lelaki yang selalu mengajariku bagaimana menyiasati hidup. Nyaris aku hanya mengenal ayah, lelaki yang selalu menjadi inspirasiku. Lelaki yang memberiku banyak kenangan, kecupan, ciuman, pelukan, dan dekap.
Delapan belas tahun sudah aku bersamanya. Sedih, bahagia, suka, duka, dan segala rasa aku telah menikmatinya. Hujatan, pujian, dan segala omongan aku sudah mengenyamnya. Sakit? Bangga? Entahlah. Semuanya ada, semuanya tiada.
“Mencintai membutuhkan kesabaran, Nak,” ucap ayahku saat itu. Aku tak mengerti apa yang dimaksudkan ayahku. Yang aku tahu, mencintai adalah kesakitan-kesakitan yang tak ada ujungnya. Rasa bahagia yang menjadi pupuk untuk memanen kesakitan nantinya. Itu yang aku pahami makna mencintai.
“Mencintai juga keikhlasan, Nak,” lanjut ayahku. Aku setuju dengan ayah kali ini. Ketika cinta sudah diembel-embeli dengan sekian ribu kepentingan, sekian juta keinginan, dan pemaksaannya maka cinta bagiku hanyalah nilai egoisme yang nanti pasti akan saling berbenturan. Seperti besi yang ditempa. Jika besi tak mau di bakar api, maka besi tak akan menjadi apa-apa. Hanya bising dan berantakan. Namun, ketika besi mau dilunakkan api, maka ia akan menjadi indah meskipun menakutkan. Seperti sebuah keris yang ayah pajang di ruang kamar.
Ah, sudahlah. Mencintai memang sebuah keanehan yang aku sendiri tak pernah mampu untuk mengurainya. Tak pernah selesai untuk mendalaminya.
Malam telah turun. Lampu sepanjang jalan sudah menyala. Ramai sesak kendaraan sudah panjang di bawah.
***
Namaku Puisi. Anak Senja, ayah memanggilku.
And who can say if your love grows,
As your heart chose?
Only time…
(Only Time – Enya)
Mungkin inilah kenyataan abu-abu.
Cinta datang tak mengenal waktu. Tidak hanya waktu, bahkan juga tempat, kondisi, atau apapun itu. Dia datang tanpa uluk salam. Di datang tak mengenal warna perasaan kita. Merahkah? Kuningkah? Birukah? Hijaukan? Atau hitam? Dia datang begitu saja. Kita tiba-tiba terkapar dan kalah.
Sudah 3 kali putaran lagu “Only Time” yang dinyanyikan Enya menggedor-gedor pikiran dan hatiku. Ah, ini terlalu naif untuk aku singkirkan. Tapi, kenapa harus dia. Ini pertanyaan besarku. Kenapa aku harus ada dalam posisi yang seperti ini. “Ayah, salahkah aku mencintaimu?”
***
“Anak… Anak Senja… Bangun!” panggilan Ayah membangunkanku.
Aku malas membuka mata. Aku bahkan makin erat memeluk guling untuk kembali menemukan kenyamanan. Mataku terlalu berat untuk dibuka. Tubuhku masih terasa lemas. Aku tak ingin kenyamananku terusik.
“Anak, bangunlah,” ucap ayah sembari mendaratkan kecupan hangat di keningku. Aku mengerjab-kerjapkan mata.
“Ayaaah…” rengekku manja. Aku lingkarkan tanganku ke leher ayah. Aku tarik ke dalam dekapan dadaku. Sebuah ciuman hangat dariku mengecup keningnya. Entah, kondisi ini yang sangat aku suka dan rindukan. Saat-saat pagi, ketika ayah membangunkanku. Aku merasakan hidup melebihi dari segala masalah hidup.
“Yah, aku hamil,” ucapku pelan dan terbata-bata.
Sesaat ayahku terdiam. DI tergeletak di sampingku. Tak lama dia bangkit Duduk persis di sampingku. Dahinya mengernyit. Namun tak lama, terlihat rona wajah kegembiraan dari wajahnya dan binar bangga menyemburat di bola matanya. Sebuah kecupan hangat kembali mendarat di keningku. Ciuman hangat menyentuh bibirku. Inilah buah dari percintaanku dan ayahku. Tentu, nantinya akan lahir Anak Puisi. Aku akan menjaganya, aku akan merawatnya, seperti ayah menjaga dan merawatku. Dia anakku, anak dan cucu ayahku.
***
Anakku adalah anak dan cucu ayahku. Anak Puisi. Yang lahir dari rahim kata-kata. Percintaanku dengan ayah tercipta di tengah malam yang khusuk. Dzikir angin dan tarian daun telah mengantarku pada puncak ekstase yang luar biasa. Dalam percintaan, aku telanjang kata, liarnya imaji memompa jantungku berdetak lebih cepat. Melebihi detak putaran waktu. Peluh berjalan melintas di setiap tubuku dan tubuh ayahku yang sudah penuh dengan gelimang aksara.
Gelora aku dan ayahku berlahan-lahan terus meniti satu-persatu kehangatan kalimat, menurunkan makna pada simbol-simbol yang kubangun. Mencengkeram erat di punggung baris, menari erotis di sepanjang bait. Percintaanku dengan ayah telah melahirkan kebinalan pikiran dan rasa yang tak berkesudahan. Kenangan indah lahir di setiap jejak kata.
Akulah puisi. Lahir dari rahim kata-kata atas percintaanku dengan ayahku yang lantas melahirkan anakku, Anak Puisi.
“Selamat ya, Nak. Ayah bangga padamu. Kamu sudah menjadi ibu sekarang.”
“Makasih, Ayah!” ucapku.
Sebuah kecupan hangat mendarat di kening dan kedua pipiku. Pun bibirku. Aku makin erat memeluk Ayah. Entah, apa yang aku rasakan saat ini. Jantungku berpacu kencang. Seluruh sendi-sendiriku terasa lemas. Pelukan ini sungguh membuatku menjadi manusia. “Aku ingin menjadi ibu yang sesungguhnya.”
Tergeletak sebuah buku, hadiah ulang tahunku, buah percintaanku dengan ayahku, yang kini ada di atas mejaku. “Namaku Puisi.”
***
Jakarta, 1 Mei 2016
Biodata Penulis:
Handoko F Zainsam. Lelaki kelahiran Madiun 6 Oktober ini merupakan penggagas dan pendiri Komunitas Mata Aksara, CK Writing – Jakarta, dan menjadi salah satu pendiri Perhimpunan Sastra Budaya Negara Serumpun (PSBNS) 6 Negara. Karya-karyanya antara lain I’m Still A Woman—Tahun 2005 (Novel). Kota Sunyi Tahajud Cinta Kunang-Kunang—Tahun 2009 (Puisi); Ma’rifat Bunda Sunyi—Tahun 2010 (Puisi). “Love in Anomaly” Tahun 2013 (Kumpulan Cerita), “Suluk Nang! Ning! Nung!”— Tahun 2014 (Puisi), “Dua Tanda Kurung” (Novel)—Tahun 2016, “Risalah Suwung”—Tahun 2016(Puisi). Beberapa karya seperti esai, puisi, cerpen, dan opini juga terbit dalam beberapa judul buku dan juga dimuat di berbagai media massa.